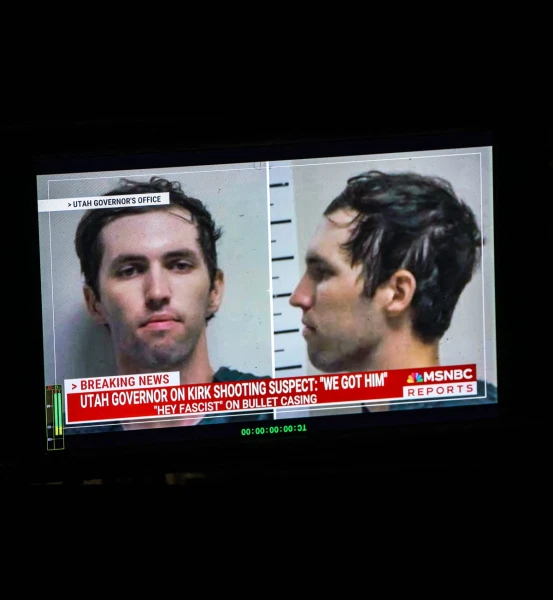Oleh: Fadjar Pratikto
Zhongnanhai—kompleks pemerintahan tertinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang terletak di jantung Beijing—kembali menjadi pusat perhatian dunia. Sejak awal Juli 2025, sejumlah sinyal politik yang dilemparkan ke ruang publik memicu spekulasi besar: apakah Xi Jinping, sosok kuat yang memimpin Tiongkok sejak 2012, tengah bersiap melepas kekuasaannya? Atau ini hanya bagian dari strategi konsolidasi ulang, seperti yang kerap terjadi dalam sejarah kekuasaan otoriter?
Artikel terbaru South China Morning Post (SCMP), yang terbit 6 Juli lalu, menjadi katalis dari spekulasi ini. Dalam artikelnya, SCMP menyebut bahwa aturan baru hasil rapat Politbiro PKT pada 30 Juni lalu “mengisyaratkan Xi Jinping mulai melepas lebih banyak kekuasaan”. Ini adalah bahasa isyarat yang tidak biasa untuk media yang selama ini dikenal berhati-hati—terlebih sejak berada di bawah kendali Alibaba Group, yang memiliki hubungan erat dengan Beijing.
“Angin dari Selatan”: Tanda-Tanda dari Dua Media
Di kalangan pengamat Tiongkok, SCMP memiliki reputasi sebagai penebar “signal leak” atau sinyal politik terselubung dari elite Beijing. Artikel yang membahas peraturan baru tentang mekanisme kerja lembaga pengambilan keputusan pusat PKT itu, oleh banyak pihak dibaca sebagai pesan kode: Xi sedang menyiapkan fase baru, entah berupa transisi kekuasaan atau rekalkulasi posisi dalam struktur elite.
Yang menarik, SCMP tidak secara gamblang menyatakan bahwa Xi akan mundur. Sejumlah komentator anonim menguatkan sinyal itu dengan menyebut bahwa “ini adalah fase kritis menuju pensiun”. Namun narasi lain tetap disisipkan: bahwa Xi hanya membagi beban kerja, bukan melepas kekuasaan.
Di balik kontradiksi ini, ada satu benang merah: sistem kekuasaan di Zhongnanhai sedang bergerak. Apakah ini pergerakan lembut menuju transisi, atau manuver memperpanjang kekuasaan, masih menjadi teka-teki.
Sementara SCMP melemparkan “angin” dari dalam sistem, The Epoch Times—media berbahasa Mandarin yang berbasis di luar negeri dan dikenal sebagai kritikus keras PKT—memberikan perspektif tajam dari luar. Dalam sejumlah laporannya, The Epoch Times mengaitkan absennya Xi dan perubahan peraturan PKT dengan tekanan internal yang semakin kuat, terutama dari faksi-faksi lama dalam militer dan kepartaian.
Epoch Times bahkan menyebut skenario terburuk sedang menghantui elite PKT: bayang-bayang tragedi Soviet. Pembelahan elite, kegagalan ekonomi, dan keresahan sosial digambarkan sebagai bom waktu yang hanya menunggu momen ledakan.
Isyarat lain menurut The Epoch Times yang memperkuat spekulasi adalah absennya Xi Jinping dalam forum internasional. Pada KTT BRICS di Brasil, 6–7 Juli lalu, Xi tak hadir. Sebagai gantinya, Perdana Menteri Li Qiang mengambil alih peran diplomatik dan bahkan melanjutkan lawatan ke Mesir.
Secara resmi, ketidakhadiran Xi disebabkan benturan agenda. Namun hingga pertengahan Juli, Xi hanya menjalani kunjungan domestik ke Provinsi Shanxi—kegiatan yang secara diplomatik bisa dengan mudah dijadwal ulang. Ketidakhadiran Xi di panggung global justru terlihat seperti penghindaran yang disengaja. Epoch Times menyebutnya kekuasaan Xi sudah dipreteli.
Momen Kritis: Parade 3 September dan KTT Shanghai
Dua momen penting dalam kalender kekuasaan Xi Jinping akan menjadi penentu: Parade Militer 3 September untuk memperingati Kemenangan Perang Anti-Jepang, dan KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).
Jika Xi hadir dan tampil sebagai inspektur pasukan—peran simbolik tertinggi pemimpin Tiongkok—maka itu bisa dibaca sebagai upaya menegaskan bahwa ia masih in control. Namun jika ia kembali absen, maka narasi transisi kekuasaan akan mendapat pembenaran kuat.
Sejarah selalu menjadi kaca benggala para elite. Bagi PKT, bubarnya Uni Soviet menjadi peringatan abadi. Dari kematian Stalin, kejatuhan Khrushchev, hingga kudeta gagal terhadap Gorbachev pada Agustus 1991—semuanya menampilkan satu pola: transisi kekuasaan yang kacau bisa menghancurkan sistem yang tampaknya kokoh.
PKT belajar dari semua itu. Dalam kasus kudeta gagal 2012 yang melibatkan Zhou Yongkang, Xi bergerak diam-diam: stabilitas tetap dijaga, dan pembersihan baru dilakukan saat kekuasaan sudah solid. Model ini yang kini terlihat diulang—jika memang benar ada proses transisi.
Namun tantangan hari ini jauh lebih besar. Ketidakpuasan rakyat meningkat di tengah tekanan ekonomi, masalah keamanan pangan, dan skandal layanan publik. Dunia maya di Tiongkok menjadi tempat ledakan emosi yang tak terkendali—semacam katup tekanan yang bisa meledak jika transisi kekuasaan tidak dikelola dengan hati-hati.
Zhongnanhai di Persimpangan
Apa yang terjadi di balik tembok merah Zhongnanhai kini lebih misterius dari biasanya. Kekuatan Xi yang selama ini dominan, mulai menunjukkan keretakan kecil. Apakah ini disengaja demi menjaga stabilitas? Atau ini awal dari kejatuhan perlahan?
Tidak ada yang benar-benar tahu kapan dan bagaimana kekuasaan di Tiongkok berpindah tangan. Namun satu hal pasti: sistem politik di Tiongkok sangat sadar sejarah. Mereka tahu betul bahwa satu langkah salah bisa mengulang nasib Uni Soviet.
Sebagaimana tulis The Epoch Times, “Xi tengah berada di persimpangan jalan: melanjutkan otoritarianisme dengan risiko krisis sosial besar, atau membuka pintu transisi dengan risiko kehilangan kendali.” Pilihan mana pun akan berdampak tidak hanya bagi Tiongkok, tetapi bagi seluruh dunia.
Parade 3 September akan menjadi panggung penentu: apakah Xi Jinping tampil untuk terakhir kalinya sebagai Kaisar Merah? Atau justru menunjukkan bahwa “macan” masih bertaring?
Dunia hanya bisa menunggu. Sementara itu, para pembaca yang cermat harus terus belajar membaca arah “angin” dari Beijing—karena seperti kata pepatah klasik Tiongkok, “Suara genderang yang keras tak selalu berarti perang, kadang ia menyembunyikan pesan lembut yang paling menentukan.”