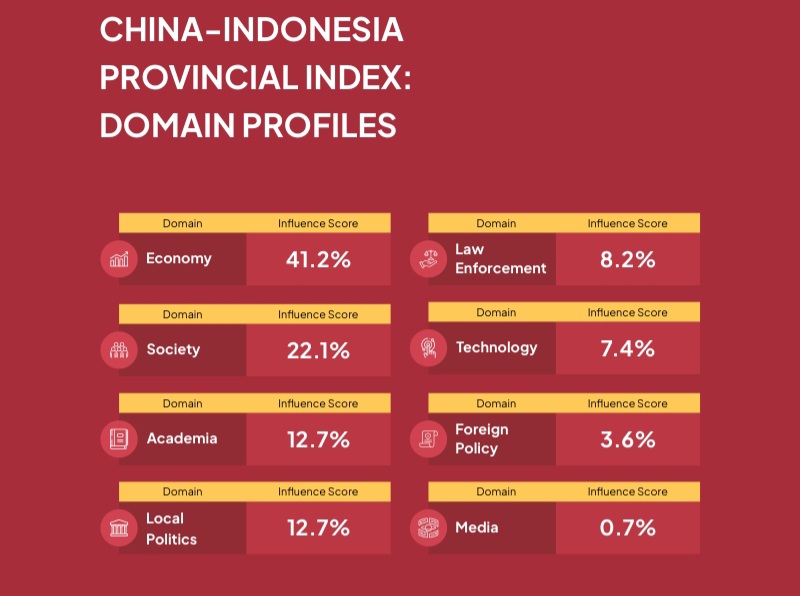Oleh: Fadjar Pratikto
Peristiwa 30 September 1965 (G30S/PKI) merupakan salah satu titik balik sejarah paling kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tragedi berdarah ini menewaskan enam jenderal Angkatan Darat dan membawa implikasi besar: jatuhnya Presiden Soekarno, hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI), serta lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Di balik semua itu, pertanyaan yang terus mengemuka hingga kini adalah sejauh mana keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam peristiwa tersebut. Analisis ini berusaha menelusuri jejak ideologis, diplomatis, dan praktis yang menghubungkan Jakarta–Beijing pada dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an, dengan merujuk pada berbagai sumber: arsip sejarah, kesaksian akademisi, hingga kajian geopolitik global.
Sukarno, PKI, dan Poros Jakarta–Peking
Sejak dekade 1950-an, Soekarno mengembangkan politik luar negeri yang dikenal sebagai politik mercusuar dan poros anti-imperialisme. Ia melihat dunia terbagi dalam dua kutub: blok Barat yang kapitalis-imperialis, dipimpin Amerika Serikat, dan blok Timur yang sosialis-komunis, dipimpin Uni Soviet serta Tiongkok.
Di tengah rivalitas ini, Soekarno mendekat ke Beijing. Hubungan Indonesia–Tiongkok semakin erat setelah kunjungan Perdana Menteri Zhou Enlai pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Sejak saat itu, terbentuklah poros politik ideologis Jakarta–Peking–Pyongyang–Hanoi. Poros ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Barat di Asia.
PKI memanfaatkan momentum tersebut. Dengan tiga juta anggota inti dan lebih dari 22 juta pengikut melalui organisasi afiliasi, PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Ketua PKI, D.N. Aidit, dikenal sebagai pengagum Mao Zedong. Ia berulang kali berkunjung ke Beijing, membawa pulang ide revolusi rakyat dan strategi perjuangan bersenjata.
Buku How the Specter of Communism Is Ruling Our World yang diterbitkan oleh The Epoch Times menyoroti fenomena global ini. Pada 1960-an, dunia berada dalam pusaran konfrontasi ideologi kapitalisme versus komunisme. Jika Uni Soviet memilih jalur diplomasi dan kompromi pasca-Stalin, Mao justru mendorong revolusi keras. Ia mengkritik Moskwa sebagai “revisionis” dan mendorong partai-partai komunis di Asia Tenggara untuk melakukan revolusi kekerasan.
PKT aktif mengekspor revolusi melalui berbagai cara: dukungan finansial, pelatihan militer, hingga pengiriman senjata. Dalam konteks Asia Tenggara, PKT mendukung pemberontakan komunis di Malaya, Vietnam, Laos, hingga Filipina. Dampaknya menyakitkan: ribuan diaspora Tionghoa perantauan dicurigai sebagai agen PKT, sehingga mereka menjadi sasaran diskriminasi, pembatasan, hingga pembantaian etnis di berbagai negara.
Indonesia menjadi salah satu ladang utama penetrasi ideologi PKT. Aidit dan pimpinan PKI memperoleh bantuan moral dan material dari Beijing. Mao, menurut catatan sejarah, berulang kali menekankan pentingnya Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis di Asia Tenggara.
Selain jalur partai, hubungan pribadi Sukarno dengan Beijing juga cukup dekat. Pada pertengahan 1960-an, kesehatan Sukarno menurun drastis. Pemerintah Tiongkok mengirimkan tim medis untuk merawatnya. Bantuan ini memperlihatkan betapa pentingnya Sukarno bagi Beijing sebagai sekutu strategis di Asia Tenggara.
Namun, kondisi kesehatan Sukarno yang melemah justru membuatnya semakin sulit mengendalikan dinamika politik domestik. Tarik-menarik antara Angkatan Darat yang anti-komunis dan PKI yang semakin radikal berakhir dengan tragedi 30 September.
Keterlibatan Beijing dalam G30S juga sering ditarik dari pertemuan rahasia Mao dengan Aidit. Hal ini diungkapkan dalam buku “Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, dan Etnik Tionghoa 1945–1947” karya sejarawan Taomo Zhou.
Dalam diskusi yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2019, Prof. Dewi Fortuna Anwar mengutip transkrip percakapan Mao–Aidit dari arsip PKT, bertanggal 5 Agustus 1965. Dalam percakapan itu, Mao bertanya tentang strategi PKI, sementara Aidit menyatakan rencana untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Mao mendukung semangat revolusi, tetapi tidak mengetahui kapan aksi itu akan dilakukan.
Prof. A. Dahana, penerjemah arsip, menegaskan: percakapan itu menunjukkan Beijing tidak terlibat langsung dalam G30S. Namun, dukungan ideologis dan moral dari Mao terhadap Aidit sangat jelas. Bagi Mao, kematian Aidit pasca-G30S adalah kehilangan besar. Ia bahkan menulis sebuah puisi eligi, menggambarkan Aidit seperti bunga mawar yang mekar lalu gugur menjelang musim semi.
G30S, Suharto, dan Putusnya Hubungan Jakarta–Beijing
Setelah enam jenderal terbunuh pada 30 September 1965, Jenderal Soeharto bergerak cepat. Ia menumpas gerakan tersebut, menuduh PKI sebagai dalang, dan secara sistematis menghancurkan partai itu bersama jaringan afiliasinya.
Soeharto kemudian memutus hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Beijing dituduh mendalangi G30S, meskipun bukti langsung atas keterlibatan operasional PKT tidak pernah terungkap secara meyakinkan. Hubungan Indonesia–Tiongkok membeku selama 23 tahun, baru dipulihkan kembali pada 1990.
Ekspor revolusi PKT juga meninggalkan luka panjang bagi diaspora Tionghoa di Indonesia. Setelah G30S, banyak orang Tionghoa dicurigai berafiliasi dengan PKI atau Beijing. Diskriminasi, pelarangan budaya, hingga kekerasan etnis mewarnai masa Orde Baru.
Pernyataan Zhou Enlai dalam forum internasional, bahwa Beijing bisa “mengekspor komunisme melalui orang Tionghoa perantauan”, memperkuat kecurigaan itu. Akibatnya, komunitas Tionghoa Indonesia menjadi korban sampingan dari rivalitas global yang sebenarnya mereka tidak kendalikan.
Peristiwa 1965 adalah simpul dari berbagai faktor: konflik internal Angkatan Darat–PKI, kesehatan Sukarno yang memburuk, serta rivalitas global kapitalisme–komunisme. Tiongkok, melalui PKT, memang tidak terbukti secara langsung mendalangi G30S. Namun, inspirasi ideologis, dukungan material, dan kedekatan Aidit–Mao menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.
Meski peristiwa sudah berlalu 60 tahun, sejauh ini sejarawan masih berdebat mengenai peran PKT dalam G30S. Ada dua arus besar:
1. Pandangan keterlibatan langsung – menilai bahwa dukungan finansial, militer, dan ideologis PKT terhadap PKI menjadikan Beijing bagian dari persekongkolan G30S.
2. Pandangan keterlibatan tidak langsung – menekankan bahwa Beijing hanya sebatas memberi inspirasi ideologis, tanpa mengetahui detail operasional. Bukti percakapan Mao–Aidit justru mendukung pandangan ini: Mao mendorong revolusi, tapi tidak tahu kapan G30S akan terjadi.
Terlepas dari itu, konteks geopolitik menunjukkan bahwa Asia Tenggara pada 1960-an memang menjadi ajang perebutan pengaruh antara kapitalisme dan komunisme. Indonesia, dengan PKI yang masif, berada di garis depan pertarungan ideologis tersebut.
Bagi Indonesia, tragedi ini mengajarkan bahwa politik luar negeri dan aliansi ideologis tidak pernah lepas dari konsekuensi domestik. Sementara bagi diaspora Tionghoa, 1965 menandai awal dari puluhan tahun diskriminasi akibat kecurigaan politik yang diwariskan oleh konstelasi geopolitik Perang Dingin.
Sejarah mencatat bahwa hubungan Jakarta–Beijing baru pulih pada 1990. Namun luka akibat 1965 tetap membekas, meninggalkan pertanyaan terbuka: apakah tragedi itu bisa dihindari jika Indonesia tidak terlalu dekat dengan Beijing, ataukah ia merupakan konsekuensi tak terelakkan dari pusaran perang ideologi global abad ke-20?