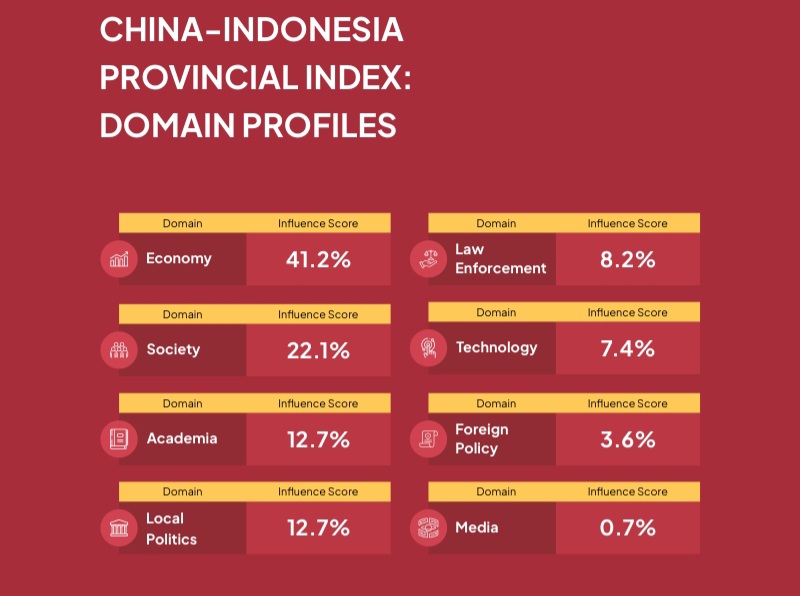JAKARTA, ADILNEWS- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menuai sorotan tajam setelah melakukan kunjungan ke Tiongkok pada awal Juli 2025. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menggali masukan dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, memimpin langsung delegasi yang mendatangi Beijing dan Shanghai guna mempelajari sistem regulasi penyiaran di negeri berpenduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa itu.
“Ini adalah kunjungan pertama KPI sejak berdiri pada 2003. Kami ingin melihat pengaturan penyiaran di China yang barangkali relevan dengan situasi di Indonesia,” ujar Ubaidillah dalam pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, pada 1 Juli 2025.
Turut hadir dalam rombongan antara lain para komisioner KPI Pusat seperti Tulus Santoso, Muhammad Hasrul Hasan, dan Aliyah. Kedatangan mereka disambut Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Kepala Perwakilan Parulian Silalahi, serta jajaran staf KBRI. Sekitar 50 mahasiswa dan warga Indonesia di Beijing juga hadir mengikuti diskusi tersebut.
Delegasi KPI lebih dulu mengunjungi Shanghai Media Group (SMG), kemudian bertolak ke Beijing untuk berdiskusi dengan China Media Group (CMG) dan The National Radio and Television Administration (NRTA). Dua lembaga ini dikenal sebagai perpanjangan tangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang mengawasi seluruh ekosistem penyiaran — dari radio, televisi, hingga platform digital.
Menurut Ubaidillah, studi banding ini penting agar KPI mendapatkan perspektif baru tentang regulasi media digital. “Selama ini kita hanya melihat ke Eropa atau Amerika. China juga menarik karena jumlah penduduknya besar dan hubungan Indonesia–China semakin dekat,” jelasnya.
Namun, langkah KPI ke Tiongkok justru memicu kekhawatiran publik. Banyak pihak menilai Tiongkok bukanlah contoh ideal, mengingat model penyiaran di sana sangat terpusat dan dikendalikan penuh oleh partai berkuasa. CMG dan China Global Television Network (CGTN) secara terang-terangan bertugas menyiarkan narasi resmi pemerintah, sedangkan NRTA yang setara kementerian berfungsi sebagai regulator sekaligus pengawas ketat agar semua konten sesuai arahan propaganda negara.
“Belajar ke Tiongkok boleh saja, tetapi meniru polanya jelas berbahaya. Sistem penyiaran di sana hanya menjadi corong propaganda, bukan wahana aspirasi publik,” ujar R. Pudiyanto, mantan pengelola radio lokal.
Sistem sensor di Tiongkok memang jauh berbeda dengan nilai-nilai pers Indonesia. Lembaga penyiaran di sana berada di bawah subordinasi penuh negara, dan kebebasan berekspresi nyaris tak punya ruang. Konten yang memuat kritik atau laporan investigasi sensitif praktis tidak punya tempat untuk tayang.
Kekhawatiran itu muncul seiring munculnya sejumlah pasal bermasalah dalam draf revisi RUU Penyiaran yang saat ini digodok DPR. Salah satunya adalah perluasan kewenangan KPI untuk menangani sengketa jurnalistik penyiaran, padahal sejak lama urusan sengketa jurnalistik menjadi ranah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain itu, publik juga menyoroti pasal yang melarang penayangan jurnalistik investigasi secara eksklusif. Padahal, karya investigasi merupakan napas utama kebebasan pers untuk membongkar penyalahgunaan kekuasaan.
Tak hanya itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) juga menyoroti draf RUU Penyiaran tertanggal 27 Maret 2024. SAFEnet menilai, beberapa pasal dalam rancangan tersebut berpotensi memperluas kewenangan KPI untuk mengatur konten di platform digital, yang justru bisa memperkuat kontrol negara atas kebebasan berpendapat warganet.
“Semangat untuk mencengkeram kebebasan berekspresi dan hak atas informasi masyarakat lewat mekanisme penyensoran ini jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia,” tegas SAFEnet dalam siaran persnya.
Belakangan, Panitia Kerja RUU Penyiaran bersama Komisi I DPR RI dan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) terus menggelar rapat dengar pendapat sejak Maret 2025. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa regulasi memang perlu diperbarui agar sesuai perkembangan zaman. Namun, kebebasan pers tetap harus dilindungi.
“Industri penyiaran sudah berubah total karena munculnya media sosial, media daring, dan konten video pendek. Regulasi harus adaptif, tapi tidak boleh mengorbankan prinsip kebebasan berekspresi,” tegas Dave.
Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik harus tetap di bawah Dewan Pers, bukan KPI, agar independensi pers tetap terjaga dan tidak terjadi konflik kepentingan. Dave meminta publik terlibat aktif mengawal pembahasan agar tidak muncul pasal-pasal karet yang bisa membungkam kritik.
Dari sisi akademisi, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat, mengingatkan bahwa revisi UU Penyiaran ini sudah diperjuangkan sejak lama. Namun ia menilai beberapa pasal dalam draf saat ini bisa mengancam kemerdekaan pers, terutama soal larangan jurnalisme investigasi.
“Investigasi adalah instrumen publik untuk mendapatkan fakta dan informasi yang mungkin tidak terungkap. Kalau itu dilarang, maka fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan akan lumpuh,” ujar Dadang.
Senada, banyak pemerhati media menilai sistem kontrol penyiaran di Tiongkok tidak cocok diterapkan di Indonesia, yang sejak era reformasi sudah menegakkan kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi.
Sistem Tiongkok memang tampak “tertib” di permukaan, tetapi harga yang dibayar adalah hilangnya ruang kritik dan hilangnya independensi redaksi. Publik khawatir jika semangat revisi UU Penyiaran meniru model otoriter seperti itu, maka rakyat Indonesia akan dirugikan karena hak memperoleh informasi objektif bisa terancam.
Di tengah masifnya perkembangan teknologi, banjir informasi palsu, dan maraknya ujaran kebencian di media sosial, revisi regulasi penyiaran memang sangat diperlukan. Namun semangatnya harus tetap demokratis, transparan, dan menghormati kebebasan publik untuk berekspresi.
KPI sebagai lembaga independen perlu mempertahankan perannya sebagai wasit yang adil, bukan alat penguasa yang mengontrol narasi publik layaknya NRTA di Tiongkok. “Literasi digital, perlindungan anak, standar kualitas program memang penting, tetapi jangan dijadikan alasan untuk mengekang kritik,” tandas Dave Laksono di DPR.
Kunjungan KPI ke Tiongkok mungkin membuka wawasan baru soal penataan industri media di negara besar, namun hasilnya tak bisa diadopsi mentah-mentah. Sebab jika yang ditiru adalah cara negara mencengkeram kebebasan warganya, maka revisi UU Penyiaran justru menjadi ancaman serius bagi demokrasi.
Sistem penyiaran Indonesia lahir dari semangat reformasi 1998, menolak pengekangan media oleh negara, dan menegaskan pentingnya suara publik. Itulah sebabnya pengawasan penyiaran harus tetap proporsional, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak boleh mundur ke belakang dengan meniru pola sensor ala Tiongkok atau terjebsk pada otoritarian informasi. Publik berharap pembahasan RUU Penyiaran berjalan terbuka dan mengutamakan kepentingan rakyat untuk memperoleh informasi yang bebas, jujur, dan independen.