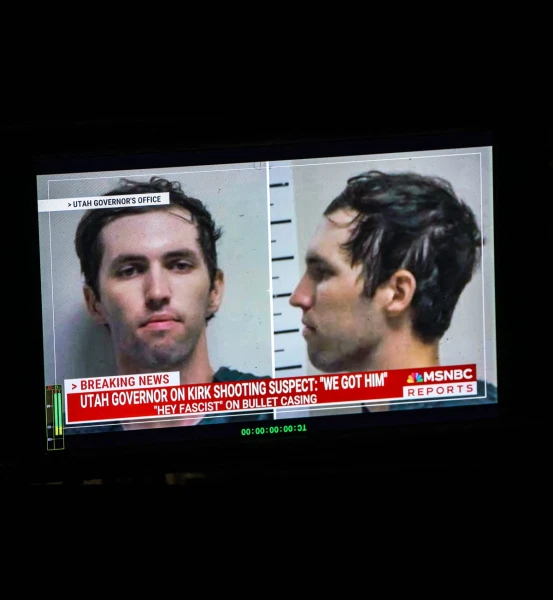Oleh:Fadjar Pratikto
Tidak banyak pemimpin di dunia modern yang mampu memusatkan kekuasaan sedemikian mutlak seperti Xi Jinping di Tiongkok. Namun kini, tanda-tanda retaknya fondasi kepemimpinan Xi semakin terlihat di tengah riak konflik internal Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan gejolak di tubuh militer. Rumor tentang lengsernya Xi, atau setidaknya melemahnya kendali riilnya, semakin menguat — sebuah fenomena langka dalam sistem politik otoriter yang terbungkus rapat oleh propaganda.
Sejak akhir 2024, absennya Xi Jinping dari agenda-agenda besar negara, bahkan dalam forum diplomatik penting, menimbulkan kecurigaan yang tak dapat dibendung. Dalam sistem PKT, di mana kultus individu dan citra pemimpin selalu dimunculkan secara masif, hilangnya sosok Xi dari pemberitaan resmi People’s Daily selama beberapa hari adalah keganjilan serius. Kesan bahwa Xi “menghilang” seolah menegaskan adanya keretakan internal yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan elite partai.
Yang lebih menarik, peran diplomasi kemudian dialihkan kepada Li Qiang dan Cai Qi, dua figur yang sebelumnya tidak menonjol dalam ranah kebijakan luar negeri. Ini seakan menyiapkan skenario suksesi secara bertahap — memberi ruang bagi figur lain mengambil alih tanpa memicu kudeta terbuka. Bahkan ketika Xi akhirnya muncul lagi untuk bertemu Presiden Belarus, Lukashenko, tata protokol yang berantakan dan tidak hadirnya penerjemah resmi semakin memperkuat dugaan bahwa kepemimpinannya sedang dipreteli oleh lingkaran dalamnya sendiri.
Pilar lain yang tampak rapuh adalah struktur militer. Sejak 2023, puluhan jenderal loyalis Xi di Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dicopot atau bahkan dilaporkan tewas dalam kondisi mencurigakan. Gelombang pembersihan besar-besaran ini menandakan pergeseran faksi di tubuh militer, yang menurut Gregory Slayton, mungkin dikendalikan oleh Zhang Youxia. Zhang, sebagai Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, memiliki jejaring luas yang bersinggungan dengan para senior partai — termasuk kubu Zeng Qinghong dan Hu Jintao.
Jika benar militer sudah tidak lagi setia pada Xi, maka prinsip “partai memimpin senjata” — yang menjadi sendi kekuasaan PKT sejak era Mao — sedang mengalami guncangan fundamental. Artinya, Xi menghadapi risiko besar: disingkirkan oleh kekuatan bersenjata yang dulu menjadi penopang utamanya.
Lebih jauh, tanda-tanda simbolik juga muncul di ranah sejarah keluarga Xi. Museum peringatan ayahnya, Xi Zhongxun, tiba-tiba diubah menjadi “Museum Revolusi Guanzhong” tanpa menyebut nama keluarga Xi. Di mata para pengamat, langkah ini lebih dari sekadar ganti nama — ia adalah sinyal politik yang tegas. Partai tampak sedang berusaha mencabut legitimasi ideologis Xi, menghapus narasi darah merah revolusioner yang menjadi basis moral kepemimpinannya.
Perubahan lain yang mengundang kecurigaan adalah kesalahan protokol yang “tak sengaja” dibuat media resmi Tiongkok pada Juni 2025, yang menyebut Xi hanya dengan nama tanpa gelar “Presiden Negara” setelah percakapan diplomatiknya dengan Donald Trump. Dalam tradisi propaganda PKT, di mana setiap kata dan gelar selalu disaring dengan teliti, kesalahan ini hampir tidak mungkin terjadi tanpa motif politik di baliknya.
Skenario paling masuk akal, seperti yang diurai Slayton, adalah Xi mulai didesak agar mundur secara halus. Dengan menjaga gelarnya tetap tertera di dokumen resmi, tetapi mencabut kewenangan nyatanya, PKT berupaya menghindari guncangan sistemik. Ini adalah pola klasik transisi kekuasaan ala Beijing — soft landing, bukan kudeta berdarah, demi stabilitas politik dan keamanan nasional.
Lalu siapa penggantinya? Nama Wang Yang semakin sering disebut-sebut di kalangan analis. Mantan Ketua CPPCC itu dinilai tokoh moderat yang tidak terlalu berafiliasi dengan faksi mana pun, sehingga relatif diterima berbagai kelompok di partai. Wang punya rekam jejak sebagai reformis dan memiliki citra bersih, cocok dijadikan “boneka kompromi” untuk meredakan ketegangan, sementara kekuasaan sebenarnya tetap dipegang para sesepuh partai dan para jenderal yang sedang naik daun.
Tentu saja, ketidakpuasan terhadap Xi bukan hanya bersumber dari dinamika politik semata. Faktor ekonomi turut memperburuk posisinya. Kebijakan “kemakmuran bersama” yang berlebihan, lockdown ekstrem era “zero COVID”, serta ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat membuat perekonomian Tiongkok babak belur. Angka utang negara yang melonjak lebih dari 50 triliun dolar AS, pasar properti yang ambruk dengan 50 juta unit rumah kosong, pengangguran anak muda yang memecah rekor, hingga eksodus investor asing — semua menjadi amunisi bagi para elite yang hendak memotong dominasi Xi.
Tak kalah genting, hilangnya kepercayaan kelas menengah — tulang punggung stabilitas rezim — menjadi momok serius. Jika tidak segera diatasi, rasa frustrasi publik berpotensi berubah menjadi letupan sosial. Dalam konteks inilah, pergantian pemimpin menjadi opsi darurat agar keruntuhan sistem tidak menyeret seluruh legitimasi PKT ke jurang kehancuran.
Bagi rakyat Tiongkok sendiri, perubahan wajah kepemimpinan seringkali tidak membawa harapan reformasi besar. Sebab, pola rezim otoriter cenderung mempertahankan status quo, hanya menukar figur di atasnya. Namun kali ini, skala masalah yang dihadapi PKT jauh lebih berat. Para tetua partai dan militer bisa jadi benar-benar mempertimbangkan langkah-langkah pembaruan ekonomi dan pembukaan politik terbatas, sebagai satu-satunya jalan menghindari revolusi sosial.
Pertanyaannya: Apakah Xi Jinping benar-benar akan tersingkir total? Sejarah PKT menunjukkan bahwa proses pergeseran kekuasaan hampir selalu terjadi tertutup, dengan sandiwara politik di permukaan. Xi mungkin masih muncul di hadapan publik, menghadiri forum-forum internasional, atau sekadar menjadi simbol.
Namun di balik layar, keputusan strategis dan kendali kebijakan akan dijalankan oleh aktor lain. Sidang pleno PKT, konferensi Beidaihe, maupun forum seperti BRICS dan Sidang Umum PBB dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi barometer. Bila Xi tak muncul di sana, atau hanya hadir sebagai “presiden tanpa kuasa”, publik akan semakin yakin bahwa masa keemasannya telah usai.
Konstelasi di tubuh militer pun wajib dipantau. Jika Zhang Youxia terus mendorong loyalisnya mengisi posisi strategis, maka dominasi Xi akan habis seiring menguatnya faksi lawan. Kombinasi tekanan ekonomi, manuver tentara, serta ketidakpuasan elite sipil, berpotensi menciptakan badai politik yang sulit dikendalikan.
Apakah ini berarti era Xi Jinping berakhir? Belum tentu seketika. Namun semua tanda menunjukkan bahwa Tiongkok sedang bersiap menghadapi fase pasca-Xi, baik dalam bentuk transisi formal atau transisi terselubung. PKT selalu menempatkan stabilitas sebagai prioritas nomor satu — sehingga apa pun skenario akhirnya, pasti diupayakan berlangsung tanpa keributan publik.
Ironisnya, Xi yang semula berambisi menciptakan stabilitas abadi justru kini menjadi sumber instabilitas, ketika kebijakannya gagal meredam gejolak di dalam negeri dan menimbulkan resistensi di lingkaran kekuasaan sendiri. Sebagai arsitek pemusatan kekuasaan, Xi pun merasakan pisau bermata dua: loyalitas yang dibangunnya bisa hilang dalam semalam ketika para jenderal dan politbiro melihatnya sebagai ancaman keberlanjutan partai.
Bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan, publik akan menyaksikan Xi tersenyum di depan kamera — tetap menjabat sebagai “presiden” — padahal kewenangan hakiki sudah beralih ke tangan lain. Itulah gaya politik PKT sejak dulu: menutup rapat perpecahan internal, sambil perlahan mencabut satu demi satu pilar kekuasaan yang dianggap membahayakan kelangsungan rezim.
Senjakalaning Xi Jinping tampaknya memang sudah mulai ditulis. Dan di sebuah negara sebesar Tiongkok, babak akhir ini akan menentukan bukan hanya masa depan Xi pribadi, tetapi juga arah masa depan stabilitas Asia dan bahkan dunia.